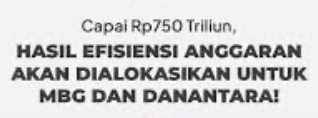Tubing Terakhir di Sungai Genting
Sebuah refleksi ekologis atas tragedi mahasiswa KKN UIN Semarang
“Bunda, kenapa bisa mereka hanyut?”.Pertanyaan itu meluncur lirih dari bibir bungsuku pagi ini, saat kami tak sengaja kompak tertarik pada satu berita di layar televisi, jelang ia berangkat ke sekolah. Ia menunjuk tiga kantong jenazah mahasiswa yang telah ditemukan setelah hanyut saat tengah mengikuti river tubing di aliran Sungai Genting, Kabupaten Kendal. Mereka adalah mahasiswa yang sedang menjalani KKN, sebuah misi pengabdian yang kini berubah menjadi duka.
Pertanyaan itu tak langsung kurespons. Dada ini seketika sesak. Di balik gelak tawa yang sempat mereka abadikan sebelum musibah itu terjadi, ada cerita tentang alam yang tak lagi tenang, tentang hujan deras yang mengguyur bagian hulu sungai, dan tentang arus yang mendadak berubah menjadi gulungan maut.
Tubing, sebuah wisata alam seru yang memacu adrenalin, membawa mereka ke tengah aliran sungai yang semula jinak. Tapi alam punya caranya sendiri untuk berubah. Saat hujan turun di hulu, air tak lagi turun sebagai kesejukan. Ia turun sebagai peringatan.
Fenomena seperti ini bukan sekadar musibah mendadak. Ini adalah akibat dari relasi yang tak seimbang antara manusia dan lingkungan. Dari hutan-hutan di hulu yang semakin menipis. Dari tanah-tanah gundul yang tak lagi mampu menyerap air. Dari perubahan iklim yang memanaskan atmosfer dan mempercepat penguapan. Semua itu berpadu membentuk hujan ekstrem yang mengguyur tanpa aba-aba, dan sungai pun meluap tanpa ampun.
Secara ekologis, peristiwa ini menggambarkan rapuhnya sistem pendukung kehidupan. Kerusakan pada sistem alami di hulu sungai berdampak langsung pada bencana di hilir. Vegetasi di daerah tangkapan air berperan sebagai penyangga hidrologis untuk menyerap, menahan, dan melepaskan air secara bertahap ke dalam tanah dan aliran sungai. Akar pohon mengikat tanah, humus menyimpan air, dan keanekaragaman hayati menjamin stabilitas fungsi ekosistem. Ketika semua itu hilang, maka daya dukung alam melemah. Sungai tidak lagi punya pelindung alami. Ketika air datang dengan kekuatan penuh, tak ada lagi yang bisa menahannya. Sungai kehilangan kendalinya, dan siapa pun yang berada di sana kini berada dalam bayang-bayang risiko.
Keenam korban bukan sekadar hanyut di sungai. Mereka tenggelam dalam ironi, ketika alam justru menelan harapan di saat mereka tengah menyulam asa demi masa depan. Dan kita, yang membaca beritanya dari kejauhan, tak bisa hanya mengirim doa. Kita harus belajar mengeja ulang tanda-tanda alam.
Di tengah krisis iklim dan kerusakan ekosistem yang terus membayangi, kita tak bisa lagi mengabaikan pentingnya restorasi lingkungan secara menyeluruh. Pemulihan hutan di daerah hulu, penghijauan dengan vegetasi asli, dan perlindungan daerah aliran sungai (DAS) bukan hanya proyek hijau, tetapi keharusan biologis untuk keberlanjutan hidup. Pemerintah daerah, pegiat lingkungan, dan masyarakat perlu bergerak bersama dalam rehabilitasi ekosistem yang kini tak lagi punya daya tahan.
“Jadi mereka meninggal karena sungainya marah?” penasaran bungsuku sebelum ia naik ke belakang motor abangnya untuk diantar ke sekolah.
Aku menarik napas, lalu menjawab, “Tidak, Nak. Sungainya tak marah. Hanya sudah terlalu lama menahan luka yang tak pernah kita rawat.” Motornya pun perlahan menjauh hingga mereka menghilang dari pandanganku. Dalam hati, lirih kuberbisik:
“Alam tak pernah mencelakai, Kitalah yang perlahan melupakan caranya bersahabat. Ya Allah, ampunilah kami yang kerap lalai menjaga titipan-Mu. Terimalah para jiwa muda yang kembali dalam pengabdian, Jangan biarkan kami terus melukai bumi-Mu, lalu berpura-pura tak mengerti saat ia menangis.” [HF].